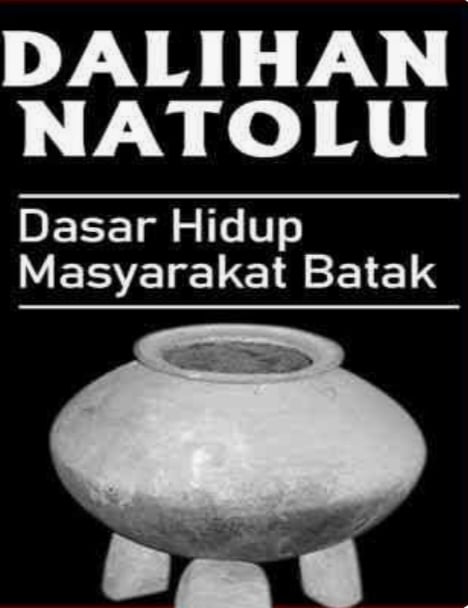Kopi Times – Di tanah Batak Toba, etika hidup tidak lahir dari buku tebal atau dogma kaku. Ia tumbuh dari dapur, dari tungku yang ditopang tiga batu. Dalihan Na Tolu, tungku yang tiga, bukan sekadar sistem kekerabatan, melainkan teologi relasi yang bekerja diam-diam dalam kehidupan sehari-hari orang Batak. Ia mengajarkan bahwa hidup hanya akan menyala bila relasi dijaga seimbang. Ketika satu batu tergeser, api padam, dan periuk kehidupan terguling.
Sebagai filsafat sosial, Dalihan Na Tolu menata hubungan manusia dalam tiga posisi, Hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru. Namun lebih dari itu, ia adalah cara orang Batak memahami Allah, sesama, dan dunia, tanpa perlu menyebutnya secara eksplisit. Dalam bahasa teologi Kristen, Dalihan Na Tolu adalah praktik iman yang terwujud dalam relasi, bukan sekadar pengakuan lisan.
Hula-hula, pemberi perempuan, dihormati melalui prinsip Somba Marhula-hula. Penghormatan ini bukan feodalisme adat, melainkan kesadaran eksistensial: hidup diterima sebagai anugerah, bukan hasil kuasa sendiri. Di sini Dalihan Na Tolu bertemu dengan teologi kasih karunia.

Seperti iman Kristen yang mengajarkan bahwa hidup adalah pemberian Allah, orang Batak diajar untuk merendahkan diri di hadapan sumber kehidupan. Mengabaikan hula-hula berarti menolak logika anugerah dan memilih kesombongan.
Dongan Tubu, sesama semarga, mengajarkan prinsip Manat Mardongan Tubu: berhati-hati, menahan ego, menjaga kesatuan. Relasi yang paling dekat justru paling berisiko melahirkan luka. Ini sejalan dengan refleksi sosiologi agama, konflik paling keras sering lahir bukan dari perbedaan, tetapi dari kedekatan. Dalihan Na Tolu membaca kenyataan ini dengan jernih. Ia tidak mengidealkan persaudaraan, tetapi mendisiplinkannya secara etis.
Sementara Boru, penerima perempuan, diperlakukan dengan prinsip Elek Marboru, dirangkul, dibujuk, dan dilindungi. Boru sering menjadi pihak yang bekerja paling keras namun paling jarang disebut. Di sini Dalihan Na Tolu menunjukkan wajah profetiknya, ia memihak pada relasi yang adil. Dalam terang Injil, sikap ini beresonansi dengan keberpihakan Yesus pada mereka yang melayani tanpa sorotan. Kekuasaan diuji bukan dari seberapa keras ia memerintah, tetapi dari seberapa jauh ia merawat yang rentan.
Sebagai sistem sosial, Dalihan Na Tolu juga berfungsi sebagai kontrol moral dan mekanisme penyelesaian konflik. Persoalan tidak diselesaikan dengan saling menyingkirkan, melainkan melalui musyawarah adat yang melahirkan padan, kesepakatan bersama yang mengikat secara etis. Ini adalah bentuk keadilan restoratif yang lahir jauh sebelum istilah itu populer dalam diskursus modern.
Dalam konteks krisis ekologis hari ini, Dalihan Na Tolu menawarkan pelajaran penting. Relasi yang timpang, antara manusia dan alam, antara kuasa dan tanggung jawab, akan selalu berujung pada kerusakan. Seperti tungku yang kehilangan satu batu, bumi pun retak ketika relasi eksploitatif dibiarkan. Dalihan Na Tolu mengingatkan, keseimbangan bukan pilihan moral, melainkan syarat keberlanjutan hidup.
Di tengah dunia yang memuja kecepatan, pertumbuhan, dan keuntungan, Dalihan Na Tolu berdiri sebagai suara pelan tapi tegas. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita kuasai, tetapi dari seberapa baik relasi kita rawat. Ia bukan nostalgia adat, melainkan etika hidup yang relevan, bagi iman, bagi masyarakat, dan bagi bumi yang kian lelah.
Seperti kopi pahit yang diminum tanpa gula, Dalihan Na Tolu tidak selalu nyaman. Tapi justru dari kepahitannya, kesadaran lahir. Dan dari kesadaran itulah, harapan untuk hidup yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih lestari bisa kembali dinyalakan. (Red/Hery Manalu)